Undang undang penistaan agama : Hampir penghujung Oktober 1998, Tabanan bergolak. Paruman (rapat) akbar digelar oleh pemuka adat, melibatkan ratusan umat Hindu setempat, menuntut Presiden Habibie memecat dan mengadili salah satu pejabat pusat. Pejabat yang dituduh melakukan penistaan agama.
Salah satu perwakilan mereka, I Gusti Gde Putra Wirasana, mengingatkan pemerintah agar secepatnya mengambil langkah. Jika tak ada tindak lanjut, Wirasana mengancam akan terjadi demo yang lebih besar lagi, juga untuk tetap menjaga citra Bali sebagai kota wisata internasional.
Bali memanas, travel warning ke Bali sempat dikeluarkan bagi turis-turis asing karena maraknya aksi protes yang sambung menyambung.
Sebelum Tabanan, Denpasar sudah lebih dahulu pecah. Disusul Bangli, Gianyar, Jembrana dan berbagai wilayah di Bali. Beberapa demo skala kecil juga terjadi di ibukota. Termasuk memberikan laporan pengaduan resmi atas penodaan agama ke Kapolri saat itu.
AM Saefuddin, Menteri Pangan dan Hortikultura era reformasi, yang saat itu juga digadang-gadang untuk maju sebagai salah satu capres dari PPP jelang Pilpres 1999 membuat pernyataan kontroversial, “Mega pernah sembahyang ke Pura. Saya salat di Masjid. Dia kan agamanya Hindu. Saya Islam. Relakah rakyat Indonesia presidennya beragama Hindu.”
Ucapan AM Saefuddin membakar amarah umat Hindu di tanah air.
Kalau Ahok perlu Buni Yani untuk memotong video penyuluhannya di Pulau Seribu yang aslinya berdurasi lebih dari satu jam menjadi 3 menit saja, maka pernyataan AM Saefuddin dilontarkannya dalam sebuah wawancara langsung yang dimuat di beberapa media cetak nasional : Republika – Suara Indonesia – Merdeka, pada tanggal 15 Oktober 1998.
Dari ancaman menutup bandara sampai ada gerakan menyarankan untuk melakukan Puputan. Puputan, semacam ritual bunuh diri ketimbang harus menyerah kepada musuh. Terus membesar menjadi ancaman disintegrasi, melepaskan Bali dari kekuasaan Republik Indonesia.
AM Saefuddin telah meminta maaf. Malah, permintaan maaf pun diulangi sampai dua kali. Tetap tak menurunkan ketegangan umat Hindu di berbagai wilayah, utamanya di Bali.
Banyak pihak menyayangkan peristiwa ini dan menuding ucapan AM Saefuddin telah dipolitisasi oleh “lawan politik”nya demi menjegal kesempatan AM Saefuddin menjadi capres pada Pilpres yang sudah di depan mata.
AM Saefuddin tergolong pejabat “bersih” termasuk dari virus korupsi. Beliau adalah tokoh akademis yang mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya di kampus IPB. Tahun 1983 – 1986, beliau menjadi rektor Universitas Ibnu Khaldun. Satu lagi tempatnya mengabdikan ilmu, Universitas Djuanda (Bogor).
Tetap saja, sebagai pejabat publik, AM Saefuddin dinilai tidak pantas merendahkan agama lain dalam kapasitasnya sebagai pelayan rakyat.
Bagaimana akhirnya?
Presiden Habibie bergeming. Tak ada pengadilan sama sekali. Tak ada reaksi dari kepolisian. Kasusnya tidak pernah ditingkatkan ke penyelidikan. Selesai begitu saja. Demo berangsur-angsur mereda dengan sendirinya.
AM Saefuddin tidak dicopot dari jabatannya. Masalah pun berlalu dengan sendirinya. Meski partai tempatnya bernaung urung menampilkan namanya sebagai salah satu kandidat capres.
Tanggal 20 Oktober 2009, Undang Undang Penistaan Agama diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna diuji konstitusionalitasnya. Salah satu argumen dari pihak yang ingin menghapus/menolak UU Penodaan Agama adalah ketentuannya yang dinilai sangat tidak jelas dan ambigu.
Tidak jelas/ambigu yang bisa diistilahkan dengan “Pasal Karet”.
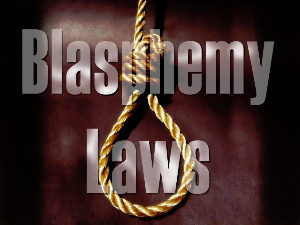
Indonesia, Punya Siapa?
Pernyataan bahwa Undang Undang Penistaan agama bisa melindungi tiap umat untuk menjalankan ibadah masing-masing mungkin cukup tepat. Tapi bagaimana jika dalam “menjalankan ibadah” ini ternyata berbenturan dengan UUD negara kita?
Soal pemilihan pemimpin misalnya. Kembali ke kasus AM Saefuddin, ada pemuka agama Islam yang mengatakan bahwa ajaran Islam melarang pemimpin non muslim. Mengundang pertanyaan lanjutan, “Tidak bisakah umat selain Islam menjadi pemimpin di Indonesia?”
Secara khusus di kasus 1998, “Tidak bolehkah umat Hindu dipilih sebagai pemimpin?”
Pernyataan Ahok di Pulau Seribu,
” … ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya oktober 2017. jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya. sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. jadi saya ingin ceritanya bapak ibu semangat. jadi gak usah pikiran, ah, nanti kalo gak kepilih, pasti, Ahok programnya bubar. gak, saya sampai oktober 2017.
jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya — dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. program ini jalan saja. ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. gak suka ama Ahok. tapi programnya, gue kalo terima, gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. jangan.”
Terlepas dari apakah Ahok telah salah atau tidak dengan membuat pernyataan di atas (yang berwarna merah), kita tidak boleh melepaskan satu hal. Bahwa pernyataan ini adalah reaksinya dari “serangan larangan memimpin muslim” yang beredar luas di masyarakat.
Misalnya, suami saya menerima pesan berantai yang isi beritanya menjelaskan tentang adanya keinginan kaum Kristen tanah air untuk menghancurkan Islam dsb dsb (yang tentu saja hoax) dengan diakhiri anjuran jangan memilih pemimpin yang beragama Kristen disertai Al Maidah ayat 51.
Reaksi Ahok menurut saya jelas. Yang ditujunya adalah “orang tertentu” (lihat warna biru) yang menggunakan ayat ini dalam pesan-pesan yang berisi kebohongan untuk kepentingan politik jelang Pilkada 2017. Tapi tetap saja, ucapannya dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik jelas tidak sesuai etiket.
Ada alibi bahwa pernyataan “non muslim tidak boleh menjadi pemimpin” vs “umat muslim tidak boleh memilih pemimpin non muslim” adalah 2 hal yang berbeda. Faktanya, kaum muslim adalah kalangan mayoritas di tanah air. Menyimpulkan bahwa kedua hal ini tidak berhubungan sepertinya janggal.
Bisakah pemerintah menjembatani hal ini?
Berbeda dengan AM Saefuddin yang masih dalam “tahap penjajakan” menuju Pilpres 1999, Ahok sebagai petahana memiliki elektabilitas cukup tinggi menuju Pilkada 2017. Apakah mungkin kita menutup mata menganggap demo-demo masif atas nama penodaan agama ini sama sekali bebas dari kepentingan politik?

Perbandingan dengan Kasus Lain
Banyak yang menjadikan contoh kasus lain sebagai perbandingan. Misalnya seorang Ibu di Bali yang kasusnya sudah sampai ke status terpidana.
Kasus bermula saat Rusgiani lewat di depan rumah Ni Ketut Surati di Gang Tresna Asih, Jalan Puri Gadung II, Jimbaran, Badung, pada 25 Agustus 2012. Saat melintas, dia menyatakan canang di depan rumah Ni Ketut najis. Canang adalah tempat sesaji untuk upacara agama Hindu.
“Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor,” kata Rusgiani seperti tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), 31 Oktober 2013.
Menurut Rusgiani, dia menyampaikan hal itu karena menurut keyakinannya yaitu agama Kristen, Tuhan tidak butuh persembahan. Rusgiani mengaku mengeluarkan pernyataan itu spontan dan disampaikan di hadapan tiga orang temannya.
Perhatikan pernyataannya. Sama sekali tidak bersayap. Menyebutkan dengan jelas obyek agama yang dituju/dihina sehingga bisa dijerat dengan Undang Undang Penistaan Agama.
Majority Privilege?
Membandingkan kasus AM Saefuddin di tahun 1998 jelang Pilpres 1999 VS kasus Ahok di tahun 2016 jelang Pilkada DKI 2017, bagaimana keduanya berlangsung dan berakhir?
Kalau dari segi pelaporan, desakan, demo yang melibatkan massa, keduanya sekilas tidak berbeda. Tapi respons pemerintah sangat berbeda. Perbedaan antara desakan yang terjadi dari umat Hindu 1998 vs umat Islam 2016 terlihat jelas dari SEGI KUANTITAS.
Jumlah pendemo Ahok jauh lebih besar dan terpusat di ibukota. Apakah hal ini yang membuat jajaran pemerintah, dalam hal ini Kapolri, melabrak Aturan Telegram Rahasia dalam Kasus Ahok?
Atau, apakah pemerintah sekarang tidak setegas pemerintahan Habibie dalam hal ini? Serta memilih untuk mengakomodir keinginan para penuntut dengan mengorbankan hukum? Ataukah karena penuntut berasal dari kalangan mayoritas sekaligus yang dituntut kebetulan adalah bagian dari masyarakat minoritas?
Semoga pemerintah tidak mengambil “jalan tengah” demi kestabilan politik semata. Karena sekali kita mengorbankan legitimasi hukum atas nama “persatuan bangsa dan negara”, siapa yang menjamin “mereka” atau kelompok lain tidak akan memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih besar. Misalnya, menjatuhkan pemerintahan yang sah di tanah air?
Sedikit renungan menjelang sidang perdana Ahok minggu depan.
***


 Follow
Follow





sudah terjadi Mbak.
Hukum sekarang ditentukan oleh unjuk massa.
Bertahun2 KKR natal di sabuga bandung tidak masalah, kemaren di demo.
Demo.
Sedih sekali.